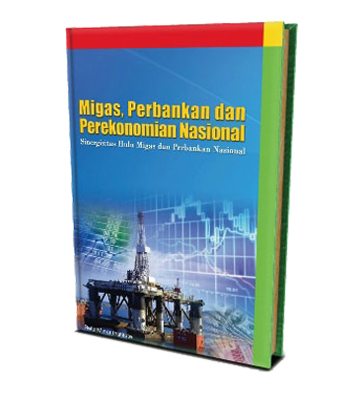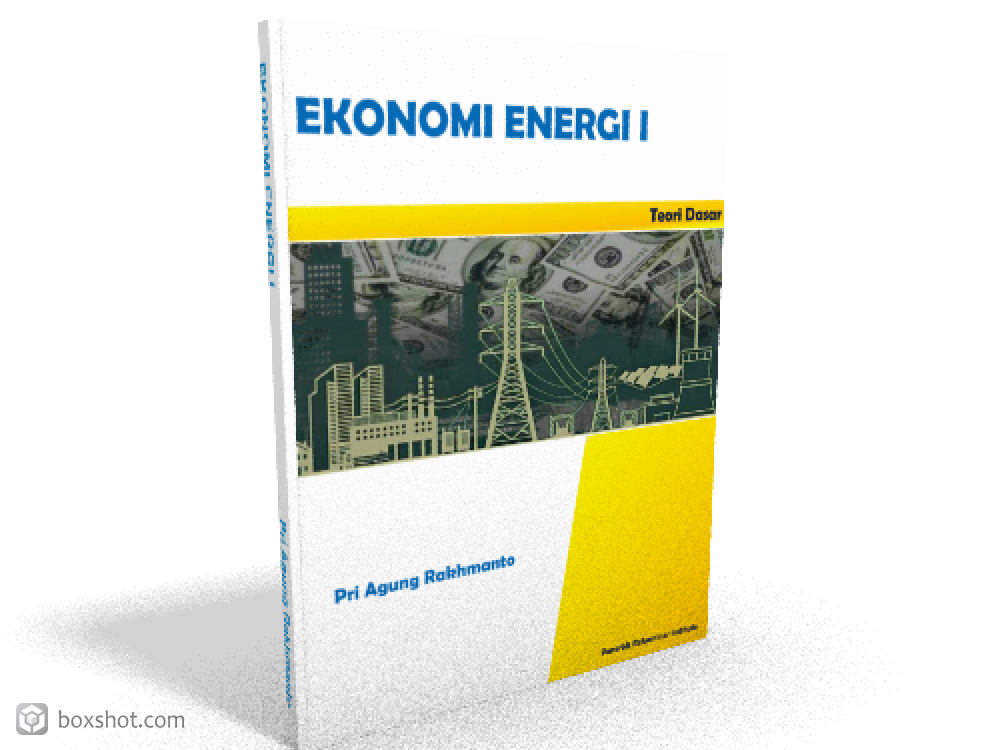Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2950 K/21/MEM/2006, maka dianggap perlu untuk menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0225K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010 – 2025.
Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010 – 2025 itu terdiri atas: (1) Peta Luas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi, Ruas Dedicated hulu, Ruas Dedicated Hilir, Ruas Kepentingan Sendiri dan Wilayah Distribusi Gas Kota; (2) Matriks Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi, RuasDedicatedHulu, RuasDedicatedHilir, Ruas Kepentingan Sendiri dan Wilayah Distribusi Gas Kota. Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0225K/11/MEM/2010, lebih lanjut dijelaskan (definisi) tentang Peta Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi, RuasDedicatedHulu, RuasDedicatedHilir, Ruas Kepentingan Sendiri, dan Wilayah Distribusi Gas Kota di bagai menjadi beberapa kategori.
Sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0225K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010 – 2025, pada periode sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Mentei yang serupa. Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 2950K/21/MEM/2006 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Jika dibandingkan, pada dasarnya secara substansi antara kedua Kepmen tersebut relatif tidak terdapat perbedaan yang berarti. Tepatnya, Kepmen No. 0225.K/11/MEM/2010 hanya merupakan pembaruan dokumen dari Kepmen No. 2950.K/21/MEM/2006.
Berdasarkan analisis substansi terhadap kedua Kepmen tersebut, ReforMiner tidak menemukan perbedaan yang mendasar. Sebagian besar pertimbangan dan dasar terhadap dikeluarkannya Kepmen No. 2950.K/21/MEM/2006 juga masih diakomodasi (digunakan) sebagai pertimbangan dan dasar terhadap dikeluarkannya Kepmen No. 0225.K/11/MEM/2010. Sementara itu substansi Ketetapan Kesatu sampai dengan Ketetapan Kesembilan dari kedua Kepmen tersebut juga relatif tidak terdapat perbedaan yang berati. Jika dianalisis lebih detail, perbedaan antara kedua Kepmen tersebut sebenarnya tidak terletak pada substansi (isi), melainkan hanya pada perbedaan sistematika.
Terkait dengan kepentingan investasi dan pemenuhan pasokan Gas Bumi domestik, pada prinsipnya para investor (pengusaha) dan masyarakat luas lebih konsen terhadap realisasi dari dokumen kebijakan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dibandingkan dengan hanya sekedar perbaikan dan pembaruan dokumen. Sayangnya, terkait realisasi Kepmen No. 2950.K/21/MEM/2006, meski setelah 4 (empat) tahun diundangkan belum ada perkembangan yang berarti tekait Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Bahkan dalam periode satu tahun terakhir. Permasalahan defisit gas nasional yang masih terus terjadi hingga saat ini, salah satu penyebab utamanya jelas ada pada minimnya realisasi dan implementasi dari dokumen Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Nasional tersebut. Oleh karena itu, realisasi terhadap semua kebijakan yang ada pada hakekatnya lebih penting dan mendasar dibandingkan hanya secara reguler pemerintah memperbaiki dan memperbarui dokumen kebijakan.
A�